Perspektif
Gamalama: Runtuhnya Wibawa Kuasa

Dentuman keras memecah suara Tarhim yang menggema di langit saat saya mengendarai sepeda motor menuju Masjid Raya Almunawar, pada Jumat 18 Juli 2025, siang kemarin. Dari kejauhan tampak panel-panel dinding almunium gedung Plaza Gamalama Modern, terlepas dan berhamburan ke jalan. Saya dan pengendara lainnya disetop, teriakan "Jangan dekat-dekat!" memecah kepanikan. Simbol kemegahan sejarah dan kekuasaan yang tinggi menjulang itu, kini sangat rapuh dan mungkin saja bisa "tumbang".
Sejarah Nusantara telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa gedung bukan hanya bangunan fisik, lebih jauh adalah metafora kekuasaan. Sejak era kerajaan Hindu-Buddha hingga kesultanan Islam, penguasa menggunakan arsitektur sebagai alat legitimasi. Lawrence Vale (2008) menulis bahwa monumen dan bangunan publik bukan hanya berfungsi secara fisik, melainkan sebagai alat simbolik yang dirancang untuk mewujudkan, meneguhkan, dan memproyeksikan dominasi politik dan identitas.
Kisah dari Jawa abad ke-9, Dinasti Syailendra membangun Candi Borobudur bukan semata tempat ziarah, melainkan simbol kosmologi yang menempatkan raja sebagai pusat semesta. Batu-batu yang disusun rapi itu adalah manifestasi derajat ketuhanan penguasa Mataram Kuno (Soekmono, 1997). Kisah lainnya, ketika Majapahit mencapai puncak kejayaan di abad ke-14, Hayam Wuruk membangun kompleks Trowulan sebagai ibu kota megah. Menurut Negarakertagama, istana dikelilingi kanal, alun-alun, dan candi yang meniru mandala kosmis. Benedict Anderson menguatkan hal ini bahwa tata ruang kerajaan Jawa selalu menempatkan istana sebagai axis mundi (poros dunia), memancarkan kekuasaan secara hierarkis ke wilayah sekelilingnya. Arsitektur menjadi bahasa bisu yang menyatakan: di sini sang penguasa.
Pola serupa berlanjut di era kesultanan Islam. Sultan Agung dari Mataram (1613–1645) membangun Masjid Agung Demak dengan atap tumpang tiga yang bukan hanya simbol tauhid, tapi juga penegasan hierarki: ratu, gusti, kawula (Lombard, 2018). Di Maluku Utara, Kesultanan Ternate mendirikan kadaton di atas bukit, menghadap laut. Posisi strategis ini, oleh Leonard Andaya, adalah pertunjukan kekuasaan dari ketinggian, di mana sultan mengawasi pelabuhan sekaligus menunjukkan dominasi atas jalur rempah. Setiap batu benteng adalah janji perlindungan, setiap jendela istana adalah mata yang mengawasi.
Sebelum menjadi Plaza Gamalama Modern, lokasi ini telah lama menjadi pusat denyut nadi perjumpaan ekonomi dan budaya. Akar sejarahnya tertanam pada Pasar Gamalama era kolonial, yang menurut Irfan Ahmad, akademisi Unkhair (wawancara Halmahera Post, 29 Desember 2020), telah aktif sejak tahun 1800-an. Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1970-an, saat pasar direnovasi menjadi bangunan bertingkat dan secara resmi dinamai Pasar Gamalama. Namun, transformasi terakhir menjadi Plaza Gamalama yang megah justru menghentikan perjumpaan tersebut.
Sejarah telah mengajarkan kita: simbol kekuasaan yang tak dirawat akan menjadi nisan kehancuran. Ketika kolonialisme merangsek, istana-istana Jawa berubah jadi museum, benteng-benteng jadi puing, hingga bangunan pasar yang mati karena kuasa. Runtuhnya Simbol dari Clifford Geertz (2000) memberikan kita pemahaman bahwa bangunan kekuasaan hanya bertahan selama otoritas penciptanya diakui. Saat kekuasaan memudar, beton megah pun kehilangan ruhnya.
Dari sejarah inilah yang membuat insiden Plaza Gamalama di Ternate begitu menusuk. Plaza modern itu, dengan panel aluminiumnya yang mengilap, seharusnya menjadi penanda kemajuan ekonomi kota. Tapi ketika ACP-nya ambrol, ia justru mengingatkan pada nasib benteng-benteng yang lapuk dimakan zaman. James Scott (1998) percaya bahwa proyek mercusuar seperti ini adalah high modernism, hasrat penguasa untuk mencitrakan diri melalui fisikalitas. Plaza Gamalama yang diidealkan sebagai simbol kemajuan dan kekuasaan, ternyata menyimpan kerapuhan.
Sejak Borobudur hingga plaza modern, siklus itu berulang. Penguasa membangun monumen untuk abadisasi nama, tapi lambat laun, hanya kekuasaan yang berbasis pada keadilanlah yang meninggalkan jejak abadi. Candi Prambanan dikenang karena cerita cinta Roro Jonggrang, bukan ambisi politik Rakai Pikatan.
Demikian pula, reruntuhan Plaza Gamalama mungkin akan lebih dikenang sebagai peringatan bahwa kekuasaan sejati bukan terpancar dari dinding yang menjulang, melainkan dari fondasi kepercayaan yang telah dibangun bersama. Sebab, “Istana boleh runtuh, tapi jalan tak boleh putus.” Demikian[].

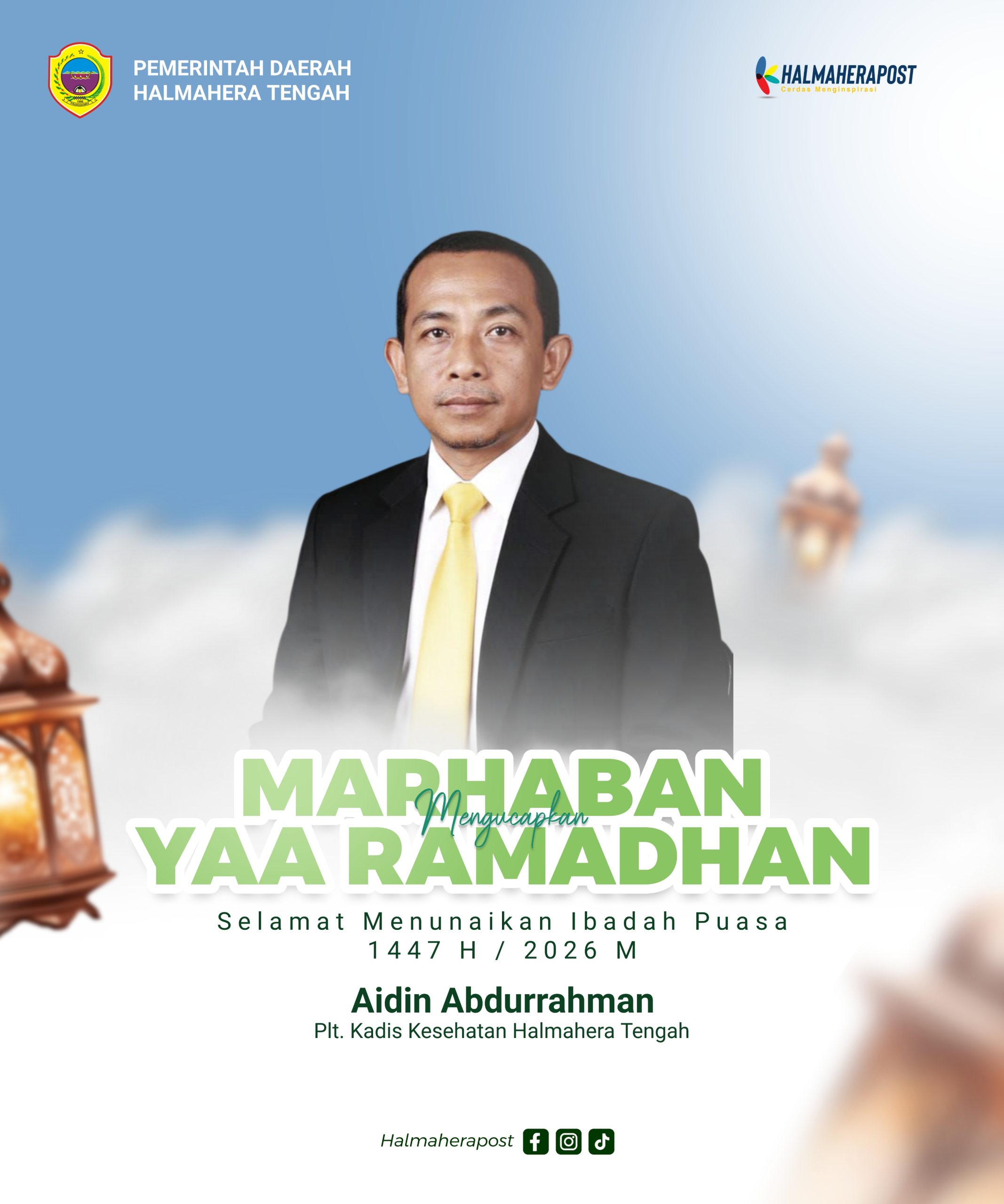










Komentar