Cendekia
“Balas Pantun” DOB Sofifi
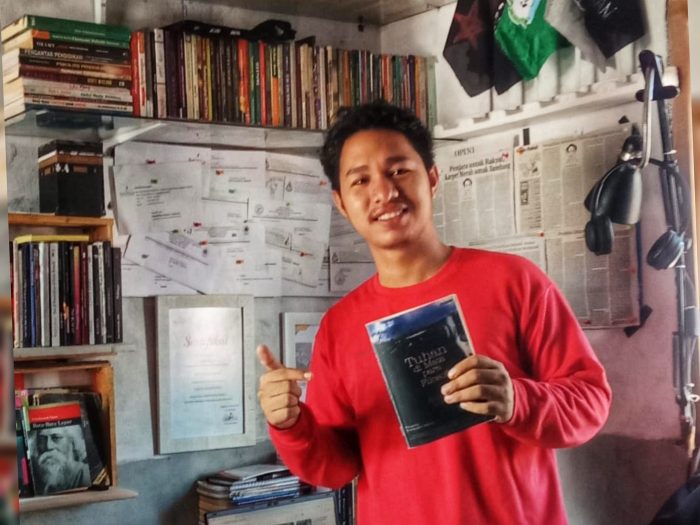
Oleh: Bachtiar S. Malawat
(Mahasiswa UNTARA)
=====================================
Akhir-akhir ini, publik Maluku Utara dikejutkan oleh kisruh pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi. Polemik ini menyeruak bak pantun politik yang dipaksa berbalas—dipenuhi kata-kata, namun kosong makna. Di tengah hiruk pikuk demokrasi lokal, narasi pemekaran muncul sebagai solusi cepat, meski jawabannya atas persoalan mendasar belum pernah benar-benar tuntas.
Pertanyaan mendasarnya tetap satu: apakah DOB Sofifi adalah jalan keluar dari permasalahan struktural Maluku Utara, atau justru jalan pintas yang menyimpan potensi ketimpangan baru di masa depan?
Pemekaran wilayah bukanlah hal baru. Sejak reformasi 1999, Indonesia mengalami gelombang desentralisasi besar-besaran. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, hingga 2022, terdapat 223 daerah otonomi baru yang terbentuk. Namun, keberhasilan DOB masih dipertanyakan. Studi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Indeks Pembangunan Daerah Tertinggal (IPDT) menunjukkan bahwa lebih dari 80% DOB mengalami stagnasi atau kemunduran dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Apakah Sofifi siap menghadapi risiko yang sama?
Sofifi memang telah ditetapkan secara hukum sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara melalui Undang-Undang No. 46 Tahun 1999. Namun, dua dekade berlalu, kota ini lebih menyerupai “kota transisi” ketimbang pusat pemerintahan. Infrastruktur jalan masih timpang, layanan dasar belum merata, dan akses transportasi sangat terbatas.
Menjadikan Sofifi sebagai DOB tanpa penyelesaian akar masalah hanya akan menambah beban fiskal provinsi. Data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan, pemekaran satu DOB bisa menyedot Rp250 hingga Rp500 miliar per tahun hanya untuk belanja birokrasi. Dalam kondisi defisit anggaran, dari mana biaya sebesar itu akan dipenuhi?
Sofifi bukan sekadar titik di peta. Ia merupakan bagian dari wilayah kultural Kesultanan Tidore yang memiliki relasi historis dan simbolik dengan rakyat. Mengubah status wilayah ini tanpa dialog budaya yang mendalam berisiko mengganggu stabilitas sosial dan menghilangkan identitas lokal.
Sejarawan Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya menulis bahwa, “kekuasaan yang memutus akar budayanya sendiri hanya akan menghasilkan kekeringan politik dan konflik terselubung.” Maka, pertanyaan yang harus dijawab: apakah pemekaran ini dilakukan dengan menghormati sejarah dan nilai-nilai lokal, atau hanya sebatas administratif?
Sering kali pemekaran wilayah dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek. Dalam Decentralization and Democracy in Indonesia (2009), Edward Aspinall menjelaskan bahwa DOB kerap menjadi alat konsolidasi patronase elite, bukan distribusi kesejahteraan.
Jika kita jujur bertanya: siapa yang sebenarnya diuntungkan? Apakah masyarakat Oba benar-benar akan mendapat akses lebih baik terhadap layanan publik? Atau hanya menjadi penonton di tengah permainan elite yang dikemas sebagai pembangunan?
Lihat Papua. Sejak pemekaran wilayah seperti Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, konflik horizontal meningkat, perebutan sumber daya makin tajam, dan fragmentasi etnis makin nyata. Komnas HAM dan LIPI mencatat tren yang mengkhawatirkan ini.
Hal serupa terjadi di Sulawesi Barat awal 2000-an. Studi Universitas Hasanuddin (2021) menyebutkan, ketimpangan antara kabupaten induk dan DOB meningkat hingga 21% dalam lima tahun pertama pasca-pemekaran. Apakah Maluku Utara ingin mengulang kegagalan yang sama?
Data BPS 2024 mencatat angka kemiskinan di Halmahera Timur dan Selatan masih di atas 19%, sementara tingkat pengangguran di Kota Ternate dan Tidore naik 4,2% dalam dua tahun terakhir. Dalam kondisi semacam ini, apakah wacana DOB masih masuk akal?
Penolakan terhadap DOB Sofifi bukan berarti menolak pembangunan. Justru, ini bentuk keprihatinan terhadap proses yang terburu-buru dan tidak inklusif. Jika ingin menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang ideal, maka yang dibutuhkan adalah pembenahan sistemik—bukan pemekaran instan.
Budaya, sejarah, dan rasa memiliki masyarakat harus menjadi bagian dari proses pembangunan. Pemekaran yang dipaksakan justru menciptakan fragmentasi sosial dan memperbesar risiko konflik horizontal. Ketika rakyat saling curiga, benih perpecahan telah ditanam. Dan jika dibiarkan, siapa yang akan bertanggung jawab?
Tulisan ini lahir dari kegelisahan atas konflik sosial, keraguan fiskal, dan lemahnya justifikasi kebudayaan dalam wacana pemekaran Sofifi. Kita tidak bisa terus membalas pantun pembangunan yang tidak berisi. Kita harus bertanya: apakah kita sedang membangun masa depan, atau sekadar mengulang kegagalan?
Mengutip Anies Baswedan: "Bagaimana rasanya melihat para elite sibuk membangun istana megah di tengah ketimpangan rakyat yang menderita?"
Sofifi bisa dibangun, tapi tidak harus dimekarkan. Ia perlu diperkuat, bukan dipisahkan. Pemekaran bukanlah bukti keberhasilan, tetapi ujian bagi kesiapan. Dan jika rakyat sudah saling baku curiga, maka DOB bukan lagi solusi.
Suba Jou. Coba pikir bae-bae soal DOB itu.











Komentar