Cendekia
Perempuan dan Minoritas, Ironi Pilkada Maluku Utara

Penulis: M. Sakti Garwan, M.Ag
Pilkada di Maluku Utara, wilayah yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan ragam budaya, menyajikan ironi dalam dinamika politik lokal yang patut dikaji lebih mendalam. Demokrasi, yang seharusnya menjamin partisipasi aktif dan kesetaraan bagi semua warga negara, justru sering terjebak dalam kenyataan sosial-budaya yang membatasi ruang gerak kelompok marginal seperti perempuan dan non-Muslim. Dengan dominasi budaya patriarki dan pengaruh kuat mayoritas agama, kesempatan kepemimpinan dalam politik terbatas bagi mereka yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang dianut masyarakat. Pendekatan interdisipliner, mencakup perspektif antropologi budaya, sosiologi politik, dan studi agama, sangat penting agar dinamika sosial dalam pilkada ini dapat diungkap secara komprehensif.
Budaya Patriarki dan Dominasi Mayoritas: Mengapa Perempuan dan Non-Muslim Terpinggirkan?
Budaya patriarki di Maluku Utara menjadi hambatan signifikan bagi perempuan untuk maju dalam pilkada. Tradisi yang menempatkan perempuan di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik mengakar kuat di masyarakat (Soekanto, 2006). Selain itu, struktur sosial patriarkal ini diperkuat oleh sistem kesultanan yang pernah/ada di Maluku Utara berabad-abad lamanya (Ricklefs, 2008). Warisan budaya serta pola pikir dalam skema kesultanan (laki-laki adalah sosok sultan) ini masih meneguhkan peran gender yang tidak setara dalam masyarakat, sehingga perempuan dianggap kurang layak untuk memimpin.
Pandangan seperti yang diutarakan oleh antropolog Soetomo (2020) mencatat bahwa “patriarki di Indonesia terutama di daerah-daerah bekas kesultanan cenderung masih memandang laki-laki sebagai pengayom utama,” sehingga perempuan tidak didorong untuk menempati posisi publik. Selain itu, dominasi agama mayoritas turut mempersempit ruang politik bagi kelompok minoritas. Identitas agama sering kali dijadikan alat politik, dan di Maluku Utara yang mayoritas Muslim, kandidat non-Muslim menghadapi tantangan besar dalam membangun basis dukungan politik yang memadai (Said, 1978).
Menurut sosiolog politik dari Indonesia, Nurhadi (2019), diskriminasi agama dan gender dalam politik lokal sering kali mencerminkan cara masyarakat melihat kepemimpinan. Dalam masyarakat yang cenderung memandang agama dan gender sebagai aspek penting dalam memilih pemimpin, peluang bagi perempuan dan non-Muslim berkurang drastis. Perspektif ini tidak hanya membuat non-Muslim sulit memenangkan pemilihan tetapi juga mempersempit ruang bagi perempuan, yang sering dianggap tidak berkompeten dalam konteks kepemimpinan formal (Habermas, 1989).
Memahami Struktur Sosial dan Kesadaran Kolektif dalam Pilkada
Struktur sosial masyarakat di Maluku Utara memainkan peran besar dalam membentuk perilaku politik warga. Budaya patriarki dan warisan kesultanan mengonstruksi masyarakat dalam kerangka sosial yang kaku, dengan status quo yang dipertahankan oleh kelompok mayoritas yang mengontrol sumber daya serta akses ke kekuasaan (Durkheim, 1982). Norma sosial yang sudah lama terbentuk menghambat perubahan, khususnya bagi kelompok yang secara tradisional tidak memiliki akses ke posisi kepemimpinan.
Sebagai contoh, perempuan dan non-Muslim menghadapi hambatan besar ketika berupaya memasuki politik, karena struktur sosial cenderung memperkuat dominasi mayoritas (Parsons, 1951). Antropolog budaya Koentjaraningrat (1990) mencatat bahwa “masyarakat Indonesia sering kali terbagi berdasarkan hierarki sosial yang tidak selalu inklusif dan cenderung mengistimewakan mayoritas.” Dalam konteks pilkada, hierarki ini mewujud dalam bentuk penolakan terhadap kandidat perempuan dan non-Muslim, di mana pandangan kolektif masyarakat menganggap bahwa pemimpin haruslah dari kalangan laki-laki Muslim.
Budaya Sebagai Penentu Cara Pandang dan Perilaku
Budaya memiliki peran sentral dalam membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap kepemimpinan politik. Di Maluku Utara, budaya patriarki dan dominasi mayoritas agama menjadi norma sosial yang secara efektif menghalangi perempuan dan non-Muslim dari partisipasi politik yang adil. Budaya patriarki ini telah berkembang selama berabad-abad sebagai bentuk adaptasi terhadap konteks historis, yang secara terus-menerus direproduksi (Harris, 1979). Meski budaya ini mungkin relevan pada masa lampau, tuntutan modernitas dan nilai-nilai demokrasi menuntut adanya tinjauan ulang terhadap norma-norma tersebut (Sahlins, 1976).
Menurut Koentjaraningrat (1982), “budaya bukanlah entitas statis, melainkan sebuah sistem nilai dan simbol yang terus berkembang dan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.” Dalam demokrasi modern, budaya patriarki serta dominasi agama mayoritas tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan, namun justru menjadi penghambat. Simbol budaya yang menguatkan posisi perempuan sebagai pengasuh dan laki-laki sebagai pemimpin masih bertahan di Maluku Utara, memperkuat norma yang menghalangi partisipasi perempuan di politik (Hofstede, 1980).
Keberlanjutan budaya yang mempertahankan nilai-nilai patriarki di Maluku Utara, yang menempatkan perempuan dalam peran domestik dan laki-laki sebagai pemimpin, juga berpotensi mempersempit peluang untuk memahami kepemimpinan dari perspektif yang lebih inklusif. Dalam konteks demokrasi modern yang mengedepankan kesetaraan, pemahaman terhadap konsep kepemimpinan, termasuk kepemimpinan non-Muslim, memerlukan interpretasi yang fleksibel. Sebagai contoh, istilah "wali" dalam tradisi Islam, seperti dijelaskan oleh Ibn Manzhur, menunjukkan adanya kelenturan makna yang dapat diadaptasi agar relevan dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.
Penafsiran atas Kepemimpinan Non-Muslim?
Ibn Manzhur dalam Lisan Al-Arab (2003) menguraikan bahwa kata wali dalam bahasa Arab mengandung berbagai makna, termasuk teman, pelindung, dan pemimpin. Penafsiran yang hanya menganggap wali sebagai larangan kepemimpinan tanpa memahami konteks historis berpotensi memunculkan interpretasi yang kaku dan kurang sesuai dengan nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan persaudaraan. Dalam konteks modern, pengertian ini sering diinterpretasikan kembali agar dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi masyarakat yang berbeda dari zaman Nabi.
Berdasarkan Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuthi (2015), larangan menjadikan non-Muslim sebagai wali muncul dalam konteks perang antara Muslim dan non-Muslim. Akrimi Matswah dalam artikel "Tafsir Kontekstual Terhadap Ayat Tentang Larangan Menjadikan Non-Muslim Sebagai Pemimpin" (2016), menekankan bahwa ayat ini diturunkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus dan bukan sebagai aturan universal. Tafsir ini menegaskan bahwa larangan tersebut tidak serta merta diterapkan pada semua situasi, terutama dalam lingkungan yang mendukung koeksistensi damai antaragama.
Dalam bukunya Tafsir Al-Mishbah (2002), M. Quraish Shihab menekankan bahwa dalam konteks negara demokrasi, asas-asas kesetaraan warga negara menjadi prioritas utama. Shihab menekankan pentingnya memahami tujuan utama hukum Islam, yakni kemaslahatan umum, daripada mempertahankan eksklusivitas agama yang berpotensi merusak persatuan masyarakat. Pendekatan Shihab ini memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum Islam yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
QS. Al-Maidah ayat 51 yang sering kali diperdebatkan dalam konteks hubungan antaragama juga perlu dilihat dengan lebih inklusif. Yusuf Qaradawi, seorang mufassir kontemporer, menekankan bahwa ayat ini harus dipahami dalam konteks sosial-politik masa Nabi, dan tidak dapat digunakan untuk melarang hubungan kerja sama antaragama dalam konteks modern yang menuntut inklusivitas (Qaradawi, 2001).
Sahiron Syamsuddin dalam Pendekatan Ma‘Nā-Cum-Maghzā (2020) menawarkan metode penafsiran kontekstual yang memadukan makna teks dan realitas sosial sebagai respons atas dinamika masyarakat modern. Metode ini memungkinkan Al-Qur'an untuk diinterpretasikan sesuai dengan nilai-nilai HAM dan tuntutan zaman. Dalam hal ini, penafsiran tentang larangan kepemimpinan non-Muslim dapat disesuaikan sehingga tidak bertentangan dengan hak asasi setiap warga negara.
Kamil (2007) dalam Syariah Islam dan HAM menekankan bahwa penerapan hukum syariah yang kaku terhadap kepemimpinan berpotensi melanggar hak-hak minoritas, terutama non-Muslim. Perspektif ini sejalan dengan asas kebebasan sipil dalam HAM yang menekankan kesetaraan semua warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks demokrasi, penafsiran yang mengedepankan keadilan dan tidak diskriminatif menjadi lebih relevan dan sejalan dengan cita-cita demokrasi.
Penolakan calon non-Muslim dalam pilkada menunjukkan bahwa perdebatan kepemimpinan tidak sekadar soal teologis, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks sosial-politik dan isu identitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana agama dan identitas dipolitisasi dalam menentukan pemimpin, sehingga perspektif yang lebih moderat dan inklusif dianggap lebih dapat menjaga persatuan dalam keragaman.
Penafsiran atas Kepemimpinan Perempuan
Sebagian ulama menggunakan penafsiran tertentu atas Al-Qur’an dan hadis untuk menyatakan bahwa perempuan tidak diizinkan memegang kepemimpinan dalam urusan publik. Ayat yang sering dijadikan rujukan adalah QS An-Nisa: 34, yang menekankan peran laki-laki sebagai "qawwam" atau pelindung bagi perempuan. Beberapa ulama, sebagaiaa ditulis oleh Ahmad Sjamsiah (1995), penafsiran tradisional tentang ayat tersebut perlu dikaji ulang mengingat konteks sosial yang berbeda pada zaman modern, yang lebih inklusif terhadap kesetaraan gender (Ahmad, 1995: 39). Penafsiran bahwa perempuan tidak dapat menjadi pemimpin mengandung nuansa patriarki yang perlu ditinjau kembali dalam bingkai yang lebih luas dan kontekstual.
Salah satu hadis yang sering dirujuk dalam perdebatan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari mengenai pernyataan Rasulullah SAW bahwa suatu bangsa tidak akan sejahtera jika menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Hadis ini dianggap sebagai dasar bahwa kepemimpinan perempuan tidak sesuai dengan prinsip kesejahteraan. Al-Asqalani (Tth.) menafsirkan hadis ini dalam konteks politik kekaisaran Persia yang dinilai cenderung korup dan otoriter, bukan sebagai larangan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan di semua kondisi. Al-Qardhawi (2001) menyarankan bahwa hadis ini mungkin lebih relevan jika dilihat sebagai kritik terhadap kondisi sosial-politik pada saat itu, bukan sebagai ketentuan yang bersifat umum (Al-Qardhawi, 2001).
Penafsiran yang menolak kepemimpinan perempuan sering kali didasarkan pada kerangka patriarki yang mempengaruhi sebagian besar tafsir Islam klasik. Fakih (1999) berpendapat bahwa tafsir-tafsir semacam ini sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki dan bukan berasal dari prinsip dasar Islam yang menegakkan keadilan dan persamaan (Fakih, 1999: 43). Engineer (2000) juga menekankan bahwa ketidaksetaraan gender dalam penafsiran agama sering kali muncul karena pengaruh budaya patriarki daripada nilai-nilai agama itu sendiri (Engineer, 2000: 121). Pandangan ini memperlihatkan bahwa konteks sosial dan budaya memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi penafsiran keagamaan, yang kadang-kadang justru bertentangan dengan semangat keadilan Islam.
Lebih lanjut, Hasyim (2001) dalam kajiannya menyoroti bahwa prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam semestinya menentang diskriminasi terhadap perempuan. Ia menekankan bahwa interpretasi yang menolak perempuan menjadi pemimpin bisa melanggar hak-hak mereka yang telah dijamin oleh ajaran Islam secara umum. Kajian yang dilakukan oleh Hasyim menemukan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dalam menjalankan tugas kepemimpinan sebagaimana laki-laki jika diberikan kesempatan yang setara (Hasyim, 2001).
Pendekatan kontekstual dalam memahami hadis ini juga disarankan oleh Mudzhar (1994) yang menganjurkan untuk melihat ajaran Islam dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda. Menurutnya, hadis yang berkaitan dengan larangan kepemimpinan perempuan dapat ditafsirkan ulang dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat yang kini lebih mengutamakan kesetaraan dan inklusivitas (Mudzhar, 1994). Kuntowijoyo (1991) juga menekankan pentingnya memahami Al-Qur’an dan hadis dengan paradigma yang dapat menggerakkan ke arah transformasi sosial yang adil (Kuntowijoyo, 1991).
Banyak ulama kontemporer menyarankan untuk menginterpretasikan ulang teks-teks agama yang berkaitan dengan isu-isu gender dengan metodologi yang lebih relevan untuk zaman ini. Minhaji (2002) menyarankan penggunaan pendekatan hermeneutik dalam menafsirkan Al-Qur’an dan hadis agar tidak terjebak pada teks secara literal yang bisa menimbulkan bias gender (Minhaji, 2002). Umar (1999) juga mengusulkan bahwa pandangan Islam seharusnya mencerminkan prinsip kesetaraan gender dengan mengedepankan penafsiran yang menekankan pada hak dan kemampuan individu tanpa membedakan jenis kelamin (Umar, 1999).
Secara keseluruhan, pandangan yang menolak kepemimpinan perempuan perlu dipahami dalam konteks sejarah, di mana nilai-nilai patriarki masih kuat. Ulama dan pemikir kontemporer seperti Shihab (1996) berpendapat bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam penafsiran, sehingga peran perempuan dalam kepemimpinan dapat dipertimbangkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Shihab, 1996). Pandangan ini memperkuat argumen bahwa penafsiran agama tidak seharusnya kaku, melainkan perlu adaptif terhadap perubahan zaman dan nilai-nilai keadilan.
Dalam Islam, keadilan dan kesetaraan menjadi prinsip dasar yang seharusnya dipegang setiap Muslim dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, interpretasi Al-Qur’an yang mendukung kesetaraan sering terhambat oleh pandangan patriarki yang mendominasi tafsir klasik. Penafsiran atas QS. An-Nisa: 34 dalam kerangka patriarkal seakan mengokohkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan publik. Namun, jika mengacu pada mufassir kontemporer seperti Amina Wadud dan Asghar Ali Engineer, interpretasi Al-Qur’an harus disesuaikan dengan konteks sosial yang lebih adil, termasuk memperhatikan kesetaraan gender (Engineer, 2001). Engineer, misalnya, menekankan pentingnya menghormati hak-hak minoritas dan keadilan sosial sebagai bagian dari pesan utama Al-Qur'an. Pendekatan progresif ini menawarkan tafsir yang lebih inklusif, tidak hanya untuk keadilan gender tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara politik.
Kekuasaan, Demokrasi, dan Keadilan dalam Pilkada
Prinsip keadilan dan kesetaraan harus menjadi fondasi utama dalam demokrasi, yang memungkinkan partisipasi setara bagi semua warga negara. Teori politik modern, seperti yang dikemukakan oleh Schumpeter (1950) dan Dahl (1971), menekankan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilihan, tetapi juga tentang keterbukaan akses politik bagi semua pihak. Di Maluku Utara, prinsip ini masih sulit tercapai karena dominasi budaya patriarki serta pengaruh agama mayoritas yang kental.
Selain itu, seperti dicatat oleh Soekanto (2006), pemahaman tentang kepemimpinan sering kali mengaitkan kekuasaan dengan identitas laki-laki Muslim, sehingga kandidat dari kalangan perempuan dan non-Muslim menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh dukungan politik. Hal ini mencerminkan bahwa dalam praktiknya, demokrasi di wilayah ini masih sebatas prosedural daripada substansial, di mana pemilu hanya menjadi ritual formal tanpa mempertimbangkan hak-hak dasar kelompok minoritas.
Mengatasi Ironi Pilkada: Menuju Masyarakat Inklusif dan Bermartabat
Untuk mengatasi hambatan dalam pilkada di Maluku Utara, diperlukan upaya kolektif dari berbagai elemen masyarakat. Pendidikan politik yang mengedepankan kesadaran hak-hak politik perempuan dan kelompok minoritas sangat penting. Upaya ini juga memerlukan kebijakan afirmatif serta dukungan dari lembaga agama yang dapat meninjau ulang tafsir-tafsir yang cenderung menghalangi peran perempuan dan non-Muslim dalam politik (Esack, 1997). Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga agama akan menjadi langkah penting menuju politik lokal yang lebih adil dan inklusif, di mana keadilan dan kesetaraan dapat terwujud.
Selain itu, peran aktif dari para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan ulama, menjadi kunci dalam mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian dan kajian yang memberikan wawasan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan kelompok minoritas dalam politik lokal, serta menawarkan solusi kebijakan berbasis data untuk mengurangi hambatan partisipasi. Di sisi lain, ulama dan ustaz memiliki peran strategis dalam dakwah yang lebih inklusif, dengan menyampaikan ajaran Islam yang mendorong keadilan dan menghargai keberagaman. Melalui ceramah dan kajian keagamaan, mereka dapat mengangkat wacana mengenai keadilan sosial yang menekankan hak-hak setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang gender atau latar belakang agama, sesuai dengan ajaran Islam yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (Esack, 1997; An-Na’im, 1990).
Referensi
- Ahmad, Sjamsiah. 1995. “Keperluan untuk Mengadakan Analisis secara Spesifik Menurut Gender.” Dalam T.O. Ihromi (peny.), Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Al-Asqalani, Muhammad ibn Ali ibn Hajar. T.t. Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari. Ttp: Dar Al-Fikr.
- Al-Bukhari, I. A. ‘Abdullah M. ibn I. ibn I. ibn B. A.-J. 2008. Shahih Bukhari. Jakarta: Maktabah al-Shafa.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. Fiqih Daulah Perspektif al-Qur'an dan Sunnah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Qardlawi, Yusuf. 2001. Fi Fiqh Al-Aqalliyat Al- Muslimah Hayat Al-Muslimina Wasat Al-Mujtama`at Al-Ukhra. Beirut: Dar al-Syuruq.
- As-Suyuthi. 2015. Asbabun Nuzul; Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- An-Na’im, A. A. (1990). Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law. Syracuse: Syracuse University Press.
- Dahl, Robert A. 1971. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.
- Darwin, Muhadjir. 2001. “Epilog: Dari Patriarki ke Kesetaraan Gender.” Dalam Muhadjir Darwin dan Tukiran (ed.), Menggugat Budaya Patriarki. Yogyakarta: Pusat Penelitian UGM.
- Djuned, M. Napis. 2006. Kamus Kontemporer Arab-Indonesia: Istilah Politik-Ekonomi. Jakarta: Teraju.
- Durkheim, Emile. 1982. The Rules of Sociological Method. New York: Free Press.
- Engineer, Asghar Ali. 2000. Hak-hak Perempuan dalam Islam. Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LSPPA.
- ———. 2001. The Rights of Women in Islam. New Delhi: Sterling Publishers.
- Esack, Farid. 1997. Qur'an, Liberation, and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression. Oxford: Oneworld.
- Fakih, Mansour. 1999. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habermas, Jürgen. 1989. The Theory of Communicative Action. Vol. 1. Boston: Beacon Press.
- Harris, Marvin. 1979. Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture. New York: Random House.
- Hasyim, Syafiq. 2001. Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam. Bandung: Mizan.
- Hofstede, Geert. 1980. Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills: Sage Publications.
- Kamil, Sukron, et al. 2007. Syariah Islam Dan HAM Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 1991. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan.
- Manzhur, Ibn. 2003. Lisan Al-Arab. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Matswah, Akrimi. 2016. “Tafsir Kontekstual Terhadap Ayat Tentang Larangan Menjadikan Non-Muslim Sebagai Pemimpin.” Suhuf 9(1).
- Minhaji, Akh. 2002. “Persoalan Gender dalam Perspektif Metodologi Hukum Islam.” Dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (ed.), Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, IAIN Sunan Kalijaga.
- Mudzhar, M. Atho. 1994. “Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam.” Dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina.
- Nur Cahyono, Edi. 2019. “Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Negara Demokrasi (Tinjauan Tafsîr Fî Zhilâl Al-Qur’ân dan Tafsîr Al-Mishbâh).” Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ).
- Parsons, Talcott. 1951. The Social System. New York: Free Press.
- Ricklefs, M.C. 2008. A History of Modern Indonesia Since c. 1200. Stanford: Stanford University Press.
- Sahlins, Marshall. 1976. Culture and Practical Reason. Chicago: University of Chicago Press.
- Said, Edward W. 1978. Orientalism. New York: Pantheon Books.
- Schumpeter, Joseph A. 1950. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Brothers.
- Shihab, M. Quraish. 1996. Wawasan Al-Qur’an. Bandung: Mizan.
- ———. 2002. Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetomo. 2020. "Gender Roles in Indonesian Society and Its Relation to Political Participation." Journal of Southeast Asian Studies 13(2): 45-57.
- Syamsuddin, Sahiron. 2017. Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur’an: Edisi Revisi Dan Perluasan.Yogyakarta: Nawasea Press.
- Umar, Nassaruddin. 1999. Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: Paramadina.
- Waluyo, Andylala. 2014. “Front Pembela Islam, Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta.” voaindonesia.com.



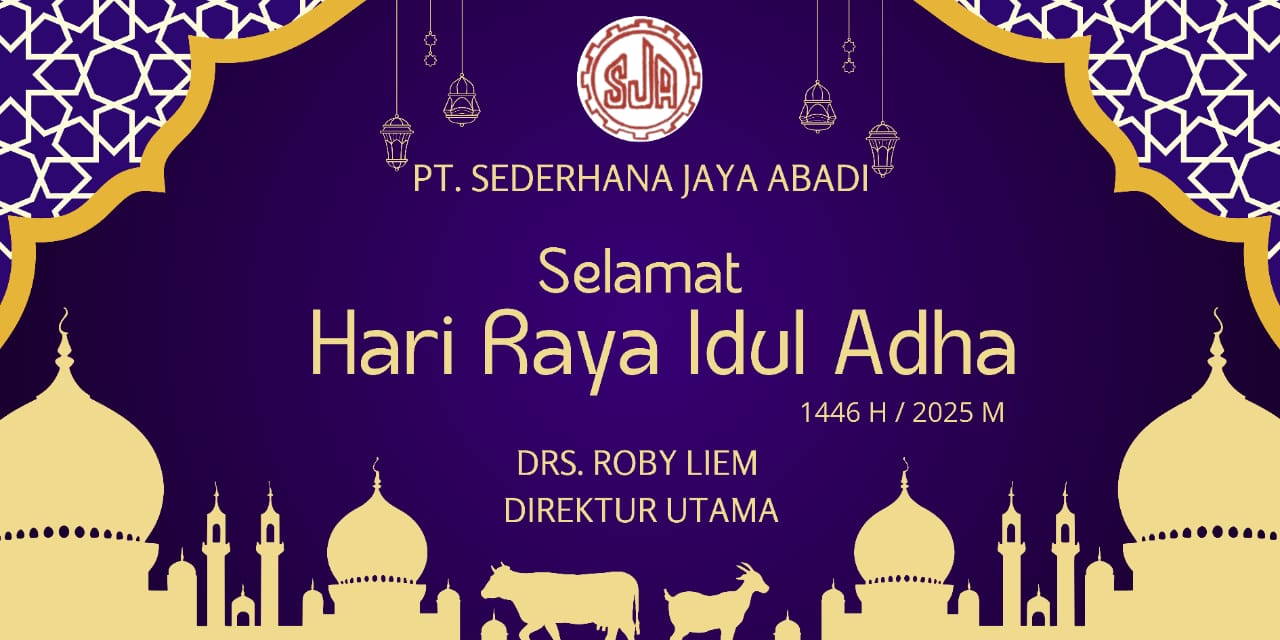










Komentar